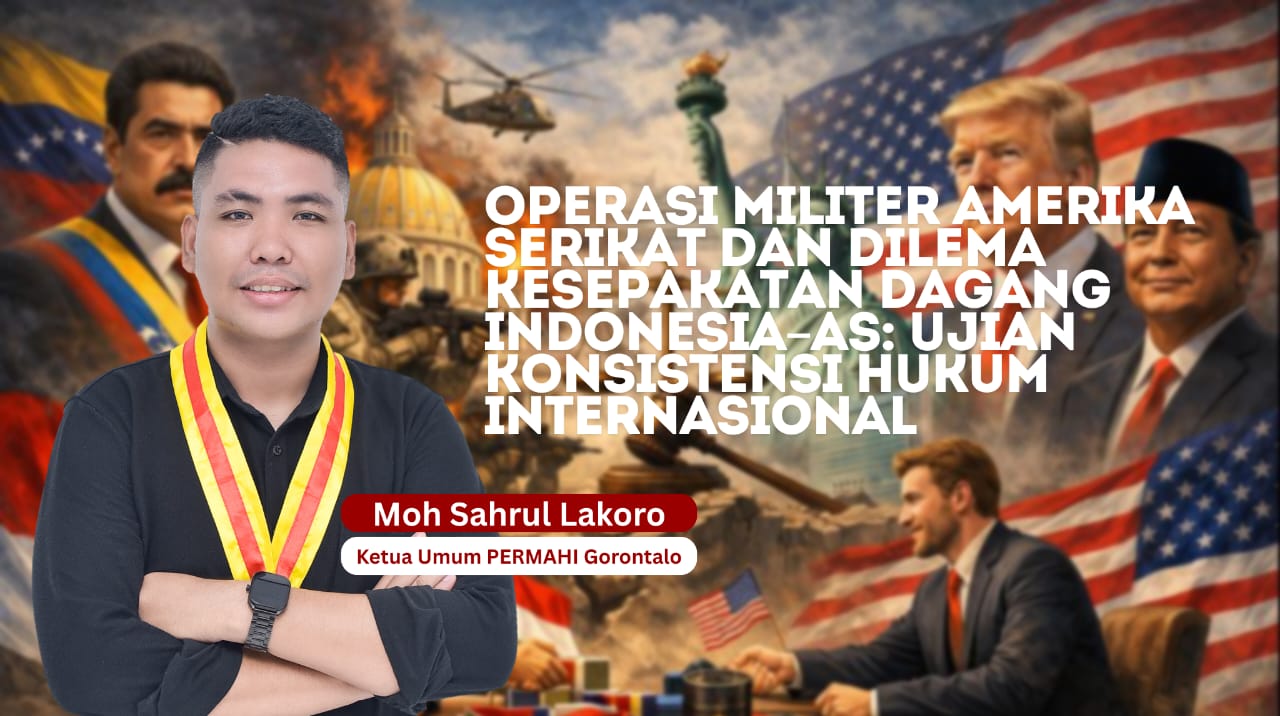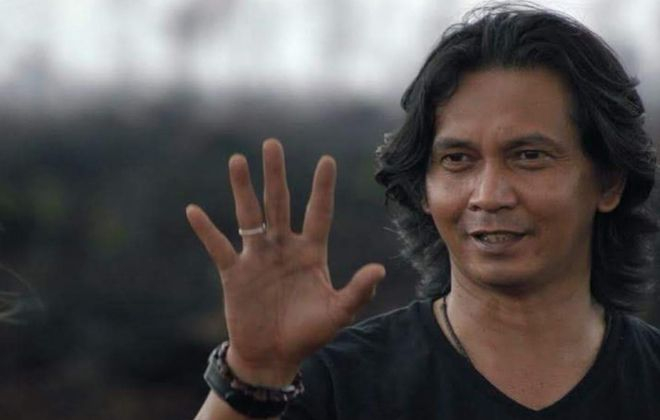Klausul Abadi Bentuk Negara dalam UUD 1945: Kesatuan yang Menjadi Harga Mati


OPINI – Setiap konstitusi modern selalu menyimpan ruh yang dijaga ketat, yakni nilai-nilai dasar yang dianggap final dan tidak boleh diganggu. Dalam hukum tata negara, hal ini dikenal sebagai eternal clause atau klausul abadi. Konstitusi Jerman misalnya, melarang perubahan yang menghapus prinsip demokrasi. Begitu pula Turki, yang melarang amandemen terhadap bentuk republik. Indonesia pun punya jalan serupa. Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”
Kalimat itu sederhana, tapi sarat makna. Ia adalah pagar yang melindungi “rumah besar” bernama Indonesia. Tidak peduli siapa yang berkuasa, sekuat apa pun tekanan politik, NKRI tetaplah berbentuk negara kesatuan. Di sinilah letak menariknya.
Di satu sisi, konstitusi modern biasanya lentur agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun di sisi lain, ada aspek yang justru dibuat beku dan abadi. Pertanyaan kritisnya: apakah klausul abadi ini sekadar simbol, atau benar-benar menjamin keberlangsungan persatuan bangsa?
Tidak mungkin memahami klausul abadi tanpa menelisik sejarah. Indonesia memang lahir sebagai negara kesatuan pada 1945. Namun, tekanan kolonial Belanda pasca-kemerdekaan memaksa bangsa ini menerima bentuk negara federal lewat Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949. Hanya beberapa bulan RIS berjalan, rakyat dan para elite menyadari bahwa federalisme lebih banyak melahirkan konflik ketimbang harmoni.
Negara bagian sibuk mempertahankan kepentingan lokal, sementara persatuan nasional justru melemah. Pada akhirnya, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan melalui UUDS 1950.
Trauma federalisme inilah yang kemudian menjadi alasan utama mengapa dalam amandemen UUD 1945 pasca-reformasi, bentuk negara kesatuan ditempatkan sebagai klausul abadi. Bagi bangsa Indonesia, kesatuan adalah “harga mati” yang tidak boleh diganggu gugat.
Bentuk negara kesatuan berbeda dari federal. Dalam sistem federal, kedaulatan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Namun dalam kesatuan, hanya ada satu pemegang kedaulatan, yakni pemerintah pusat. Daerah memang diberi otonomi, tetapi sifatnya sebatas pelimpahan kewenangan, bukan pembagian kedaulatan.
UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh, tegas menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan. Pembukaan alinea keempat bahkan memuat frasa: “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…”
Di sinilah pentingnya klausul abadi. Ia bukan sekadar pasal, melainkan konsensus politik tertinggi bahwa persatuan wilayah, bangsa, dan pemerintahan harus dijaga dalam satu bingkai.
Konstitusi Modern dan Kekakuan Klausul Abadi. Konstitusi modern biasanya dicirikan oleh tiga hal: demokratis, melindungi hak asasi manusia, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Namun klausul abadi adalah pengecualian. Ia memang dibuat kaku agar tidak bisa digoyahkan. Pertanyaannya: apakah kekakuan ini sejalan dengan semangat konstitusi modern?
Jawabannya: iya, sejauh menyangkut bentuk negara. Dalam konteks Indonesia, fleksibilitas konstitusi ditujukan untuk hal-hal teknis, seperti pengaturan pemilu, kewenangan lembaga negara, atau sistem pemerintahan. Tetapi ada hal-hal yang dipandang tidak boleh ditawar, yaitu bentuk negara kesatuan dan dasar negara Pancasila. Keduanya adalah fondasi eksistensial bangsa. Mengubahnya sama dengan meruntuhkan rumah besar yang sudah susah payah dibangun.
Adanya klausul abadi membawa beberapa konsekuensi besar diantara nya yaitu
Menutup Jalan Federalisme. Mengubah Indonesia menjadi negara federal secara hukum otomatis mustahil. Semua diskursus akademik boleh saja terjadi, tetapi secara konstitusional tidak punya ruang.
Otonomi Daerah dalam Bingkai Kesatuan. Desentralisasi yang diatur lewat UU Pemerintahan Daerah bukan distribusi kedaulatan, melainkan hanya pelimpahan kewenangan. Artinya, daerah tetap tunduk kepada prinsip kesatuan negara.
Legitimasi Melawan Separatisme. Gerakan separatis di Papua, Maluku, atau daerah lain tidak hanya dipandang mengancam politik, tetapi juga jelas-jelas melawan konstitusi. Negara punya pijakan hukum kuat untuk menolak wacana memisahkan diri.
Meski tampak ideal, klausul abadi tidak boleh dibaca secara buta, kita perlu kritis dan ada beberapa catatan:
Pertama, bentuk negara kesatuan jangan hanya dipahami sebagai simbol politik, tetapi juga harus diisi dengan substansi keadilan. Persatuan tidak akan berarti jika daerah terus merasa dianaktirikan, pembangunan timpang, dan kekuasaan tersentralisasi di satu daerah.
Kedua, konstitusi modern menuntut partisipasi rakyat. Jika klausul abadi dipakai hanya sebagai tameng untuk membungkam aspirasi daerah, maka konstitusi kehilangan ruh demokratisnya. Kesatuan tidak boleh identik dengan sentralisasi otoriter.
Ketiga, kita harus jujur bahwa bentuk kesatuan sering dijadikan alasan untuk menolak tuntutan daerah, padahal problem utamanya adalah kegagalan pemerintah pusat mengelola keadilan distribusi. Klausul abadi tidak boleh jadi alibi untuk mempertahankan oligarki kekuasaan.
Klausul abadi bentuk negara dalam UUD 1945 adalah pagar kokoh yang melindungi Indonesia dari perubahan bentuk menjadi federasi atau perpecahan wilayah. Ia lahir dari pengalaman sejarah, trauma federalisme, dan kebutuhan akan persatuan di tengah keberagaman bangsa. Dari sudut pandang konstitusi modern, klausul ini adalah pengecualian yang memang diperlukan: ia kaku, tetapi justru demi menjaga dasar fondasi negara.
Namun kita perlu melihat lebih jauh. Bentuk negara memang abadi, tetapi isi dan praktiknya tidak boleh mandek. Kesatuan harus diterjemahkan dalam keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan demokrasi yang hidup. Tanpa itu, klausul abadi hanya akan menjadi tulisan indah dalam konstitusi, tetapi kosong makna di kehidupan rakyat.
“Bentuk negara boleh diabadikan dalam teks konstitusi, tapi keadilan dan kesejahteraan hanya bisa diabadikan lewat tindakan nyata.”
Opini Oleh: Arsyadul Anam